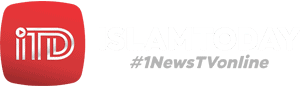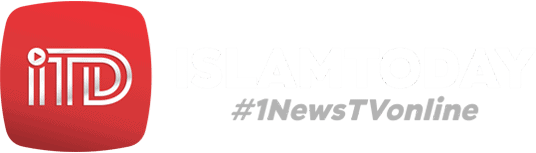(IslamToday ID) – Direktur Dhaka Forum dan salah satu pendiri CNI News Asfaq Zaman mengatakan keputusan CEO Meta Mark Zuckerberg untuk mengakhiri pemeriksaan fakta independen di platformnya merupakan upaya untuk membangun hubungan yang lancar dengan presiden baru Amerika Serikat.
Zuckerberg memang diketahui bergabung dengan Elon Musk dari Tesla, Sam Altman dari OpenAI, Jeff Bezos dari Amazon, dan Tim Cook dari Apple dalam kehadiran mereka yang patuh pada pelantikan Donald Trump.
“Di luar dari pernyataan kesetiaan ini, kebijakan Silicon Valley secara lebih luas mengisyaratkan keinginan untuk aliansi yang erat antara presiden yang akan datang dan Big Tech,” kata Asfaq seperti dikutip dari TRT World, Jumat (24/1/2025).
Akan tetapi, Zuckerberg dan kelas Tech Bro lainnya harus memahami bahwa kebijakan konten mereka memiliki implikasi yang jauh melampaui semangat budaya dan politik Amerika, sambungnya.
Memprioritaskan kemudahan perusahaan memiliki konsekuensi nyata yang berbahaya bagi individu dan negara di seluruh dunia, terutama di belahan bumi selatan.
Asfaq menuturkan bahwa selama ini, negara-negara di kawasan Afrika dan Asia Tenggara tidak lebih dari sekadar renungan bagi perusahaan-perusahaan Big Tech. Hal ini tentu mengejutkan mengingat menurut laporan SEC Facebook sendiri, 72 persen basis penggunanya berada di luar Amerika Utara dan Eropa.
“Ambil contoh skandal Cambridge Analytica. Kita tahu bahwa melalui Facebook, teknologi digital kelas militer milik Cambridge Analytica dapat memberikan gambaran palsu tentang realitas politik di seluruh dunia berkembang, dan mengubah hasil puluhan pemilu,” sebutnya.
“Anehnya, dengan ikut campur dalam pemilihan umum di Kenya dan Nigeria, misalnya, Cambridge Analytica hanya melatih algoritmanya sebelum peristiwa sebenarnya pada tahun 2016 saat pemilihan umum Amerika dan pemungutan suara Brexit di mana warga Inggris memilih Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Singkatnya, seluruh daerah pemilihan diperlakukan seperti tikus percobaan di bawah pengawasan Meta.”
Bahkan sebelum Meta baru-baru ini memutuskan untuk menghapus pemeriksa fakta pihak ketiga, platformnya telah digunakan oleh negara-negara untuk menyebarkan kampanye disinformasi yang disengaja terhadap tetangga dan pesaing mereka.
Dia lantas menyebut bila di negara asalnya, Bangladesh, mereka telah mengalaminya secara langsung. Setelah revolusi negara itu dan jatuhnya mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Bangladesh telah menjadi korban kampanye disinformasi yang terarah, yang sebagian besar menyebar melalui media sosial.
“Seperti banyak kampanye disinformasi, kampanye ini tampaknya memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh keluarnya Hasina untuk menyebarkan narasi yang dirancang untuk menjelekkan reputasi Bangladesh dan menimbulkan ketakutan di kalangan penduduk minoritas.”
“Selama revolusi, memang benar telah terjadi penyerangan terhadap kantor polisi. Ada juga (sangat sedikit) contoh kekerasan terhadap kaum minoritas. Namun, akar dari contoh kekerasan ini bukanlah rasial, tidak seperti klaim yang dikemukakan oleh berbagai akun media sosial yang terkait dengan negara. Sebaliknya, kekerasan tersebut terkait dengan hak atas tanah dan perselisihan pribadi,” dia menyebut.
Ambil contoh festival Durga Puja pada bulan Oktober, festival Hindu terbesar di Bangladesh. Perayaan Puja berlangsung tanpa kekerasan yang berarti. Namun, sedikitnya 14 rumor di media sosial tersebar antara tanggal 6 dan 12 Oktober. Menurut organisasi pemeriksa fakta sukarela Rumor Scanner, semua rumor tersebut didasarkan pada video lama atau yang telah diedit dari negara lain, sambungnya.
Dia menilai, peristiwa-peristiwa itu bukan insiden yang berdiri sendiri. Analisis dari platform intelijen Blackbird. Ai telah mengungkap dan membantah gambar-gambar yang direkayasa, yang disebarkan oleh para pendukung kepentingan tertentu di media sosial, tentang kebakaran di rumah kapten kriket Bangladesh, wanita-wanita Hindu yang ditawan, dan video-video kebakaran di restoran, dan lain-lain.
Meskipun sulit melacak penyebab dan akibat pasti dari disinformasi, banyaknya informasi menyesatkan di luar sana tidak diragukan lagi berkontribusi terhadap kebingungan dan kekacauan.
“Serangan naratif semacam ini bukanlah hal baru. Kampanye selama 15 tahun sebelumnya yang disebut sebagai Indian Chronicles dirancang untuk melemahkan negara-negara tetangga dan melayani kepentingan geopolitik dengan memengaruhi organisasi internasional melalui sedikitnya 750 media berita palsu di 119 negara,” ujarnya.
Faktanya, menurut Laporan Risiko Global 2024 dari Forum Ekonomi Dunia, risiko serangan naratif dari kawasan ini termasuk yang tertinggi secara global.
Informasi sebagai senjata Posting-posting media sosial dan artikel berita palsu ini telah dibiarkan menyebar luas di media sosial seperti api yang membakar hutan. Hal ini tidak hanya memicu ketidakpuasan sosial; hal ini dapat dan memang memicu kekerasan.
“Kita cukup melihat konflik antara penggembala dan petani di Nigeria pada tahun 2018. Bentrokan ini, yang dipicu oleh konflik sumber daya yang disebabkan oleh penggurunan, telah meningkat secara daring melalui informasi menyesatkan yang dibagikan di media sosial.”
Laporan BBC menunjukkan beberapa contoh di mana, tanpa informasi resmi, rumor tentang kekerasan penggembala, beserta gambar-gambar yang menyesatkan, telah dibagikan ribuan kali di Twitter (sekarang X). Sulit untuk memisahkan penyebaran kebencian daring dari contoh-contoh kekerasan dalam kehidupan nyata.
Penelitian telah menunjukkan bahwa misinformasi dapat sangat kuat di wilayah yang mengalami kekosongan informasi. Tanpa adanya jurnalisme independen, pengecekan fakta yang didukung, informasi menyesatkan yang disebarkan di media sosial, baik sengaja maupun tidak, dapat mengisi kekosongan tersebut dengan jauh lebih cepat dan meyakinkan.
Hal yang sama berlaku untuk laporan yang dijelaskan dalam File Facebook, yang menunjukkan bahwa Facebook mengetahui platformnya digunakan untuk memicu kekerasan namun tidak melakukan banyak upaya untuk mencegahnya.
Asfaq mengatakan bila Francs Haugen, mantan manajer Facebook dan whistleblower di balik dokumen Facebook, pernah menyatakan salah satu motivasi utamanya adalah betapa buruknya platform tersebut menangani aliran informasi berbahaya dan seruan untuk melakukan kekerasan selama perang saudara di Ethiopia.
Dengan nada dingin, dia menyatakan, “Saya benar-benar takut bahwa sejumlah besar orang akan meninggal dalam lima hingga 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan, karena pilihan dan kurangnya dana.”
Informasi yang dijadikan senjata sangatlah berbahaya. Tidak seperti persenjataan tradisional, di mana dampak dan akibatnya dapat diprediksi secara kasar, dampak informasi terhadap pikiran dapat menjadi liar dan tidak terduga, dan dapat bertahan lebih lama dari yang diharapkan. Sama seperti api yang dapat dikendalikan di awal, dengan bahan bakar yang cukup, kerusakannya menjadi eksponensial.
Meskipun tidak dapat diprediksi, disinformasi telah menjadi alat yang disukai dalam perang gagasan. Sangat sulit untuk melacak akar kampanye disinformasi, dan biaya peluncurannya relatif murah.
Faktanya, situs-situs seperti X dan Meta telah menjadi sumber berita utama bagi banyak orang; dengan lebih dari separuh penduduk Bangladesh mengonsumsi berita melalui media sosial. Studi menunjukkan bahwa di Asia Tenggara, tempat penetrasi internet sekitar 14 persen di atas rata-rata global, sifat platform yang tidak diatur ini meningkatkan kemudahan, dan risiko, penyebaran disinformasi.
Baik Meta maupun X tidak menganggap serius tanggung jawab ini. Pemeriksaan fakta independen merupakan penghalang yang lemah terhadap penyebaran disinformasi yang merusak. Menyingkirkan segala kepura-puraan moderasi konten merupakan bentuk kekeliruan yang jelas; ini merupakan pengakuan bahwa model bisnis Meta berkembang dari kemarahan, bukan akurasi.
“Di banyak kawasan di belahan bumi selatan, situs media sosial pada dasarnya merupakan layanan publik. Mengingat keuntungannya yang sangat besar, Anda mungkin berharap para eksekutif ini akan mengambil tanggung jawab ini dengan serius.”
Namun, platform ini masih dikalibrasi untuk mendapatkan keuntungan dari keterlibatan, dan tidak ada yang mendorong keterlibatan seperti kemarahan. Kebenaran atau keamanan informasi yang diberikan bahkan tidak lagi menjadi pertimbangan belakangan.
Situs seperti Meta tidak hanya gagal dalam tanggung jawab mereka terhadap pelanggan, tetapi mereka juga secara aktif membiarkan pengiklan papan atas menghindari prosedur moderasi konten.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi seperti Meta tidak hanya tidak tertarik untuk mengatur platform mereka, tetapi model bisnis mereka juga memberi insentif kepada mereka untuk tidak melakukannya.
Meta harus ingat bahwa pengaruhnya tidak hanya bersifat domestik, tetapi global. Media sosial masih dapat menjadi alat yang ampuh bagi mereka yang tidak bersuara dan tidak didengar. Perubahan kebijakan Meta harus mencerminkan kebutuhan dan keinginan seluruh basis pelanggannya, bukan sekadar mencerminkan suasana hati AS.
Artinya, memastikan bahwa platformnya tidak dapat digunakan sebagai senjata disinformasi, tetapi sebagai wahana wacana sipil yang andal, tepercaya, dan tidak memihak. Dengan koreksi yang tepat, Meta dan sejenisnya masih dapat membangun kembali diri mereka sebagai juara komunikasi bebas gatekeeper seperti dulu.
“Jika pemerintah dan masyarakat internasional gagal menumbuhkan keberanian, para koboi di Wild West baru akan membawa dunia begitu jauh ke dalam lubang kelinci pasca-kebenaran, sehingga kita mungkin tidak akan pernah melihat sinar matahari lagi,” pungkas pengamat tersebut. [ran]