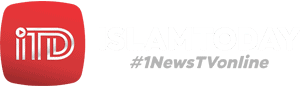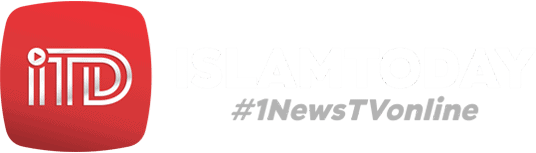(IslamToday ID) – Selama pendudukan Prancis di Aljazair, gambar-gambar sederhana digunakan untuk menanamkan propaganda brutal kepada penduduk Arab dan Berber Muslim. Desa-desa yang akan dihancurkan ditempeli poster berisi gambar sekolah dan bendera Tricolour, disandingkan dengan ibu janda dan anaknya, mayat berlumuran darah, serta rumah yang terbakar. Pilihan psikologisnya jelas: menerima “perlindungan dan perdamaian Prancis” atau menghadapi konsekuensi mematikan.
Logika kejam semacam ini kembali muncul dalam strategi Israel terhadap Palestina. Lebih dari 50.000 warga Palestina—termasuk banyak wanita dan anak-anak—telah terbunuh dalam 17 bulan terakhir. Puluhan ribu lainnya cacat akibat serangan militer Israel. Bukti menunjukkan adanya upaya genosida di mana Israel berusaha melakukan pembersihan etnis dengan dalih “membela diri”.
Gaza dan Tepi Barat kini dijadikan zona perang permanen. Hal ini dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang dianggap sebagai upaya merebut kembali wilayah Palestina yang diduduki. Militan Palestina menerobos 119 lokasi, termasuk pangkalan militer dan permukiman Israel. Hampir 1.200 warga Israel tewas, termasuk tentara, polisi, dan anggota Shin Bet. Banyak militan Palestina juga dieksekusi di tempat, termasuk oleh teknologi canggih Israel yang turut menyebabkan kematian warga Israel sendiri akibat kebijakan “Hannibal Directive”.
Di komunitas seperti Be’eri, terdapat laporan awal mengenai pemerkosaan remaja serta pembunuhan bayi dan wanita hamil, tetapi klaim tersebut terbukti tidak benar. Namun, pemerintah Israel tetap menggunakan peristiwa 7 Oktober untuk membenarkan serangan balas dendam yang menghancurkan Gaza dan Tepi Barat. Bahkan, upaya membebaskan sandera Israel yang ditahan di Gaza justru dilakukan dengan meratakan wilayah tersebut.
Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan putusan yang mengarah pada genosida serta surat perintah penangkapan bagi para pejabat tinggi Israel, serangan tetap berlanjut. Perang yang tidak seimbang ini telah berlangsung sejak 1948, saat Israel didirikan dengan dukungan penuh negara-negara Barat yang menyediakan persenjataan untuk mengokupasi tanah Palestina.
Seperti dalam perang kemerdekaan Aljazair melawan Prancis, perlawanan Palestina pun semakin kuat. Pada 1830, Aljazair mengalami invasi dari Eropa yang menyebabkan Gubernur Jenderal Prancis pertama, Thomas-Robert Bugeaud, menyatakan bahwa tanah subur harus diberikan kepada kolonialis tanpa peduli pemilik aslinya. Para kolonialis Prancis datang dari berbagai negara Eropa dengan latar belakang sulit dan memandang penduduk asli sebagai kelas bawah.
Muslim Aljazair yang menolak dijadikan pelayan mengalami penyiksaan, pemenjaraan tanpa pengadilan, bahkan pembantaian. Prancis menciptakan kamar gas primitif pertama di dunia, menggunakan asap beracun untuk membunuh massal warga Aljazair yang dianggap sebagai ancaman. Pendekatan brutal ini mirip dengan cara Israel memperlakukan warga Palestina, yang sering mereka sebut sebagai “binatang manusia” sambil menghancurkan masjid, rumah sakit, sekolah, dan apartemen di Gaza.
Mantan Perdana Menteri Israel, Golda Meir, pernah berkata, “Tidak ada yang namanya Palestina,” untuk membenarkan perampasan tanah dan penindasan tanpa akhir. Dukungan miliaran dolar dalam bentuk senjata dan bantuan terus mengalir ke Israel, yang dianggap sebagai tanah milik Meir, seorang imigran kelahiran Ukraina dan lulusan Amerika.
Perdana Menteri Israel saat ini, Benjamin Netanyahu, yang dituduh sebagai penjahat perang, bahkan mendukung rencana mantan Presiden AS Donald Trump untuk mengusir dua juta warga Palestina dari Gaza dan mengubahnya menjadi resor pantai ala Florida. Namun, sejarah membuktikan bahwa kolonialisme brutal tidak bertahan lama. Seperti Prancis yang akhirnya menyerah kepada Front Pembebasan Nasional (FLN) Aljazair pada 1962, Israel mungkin juga menghadapi tekanan internasional yang semakin berat jika terus melakukan kebrutalan terhadap Palestina.[sya]