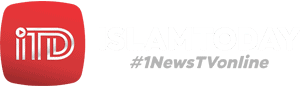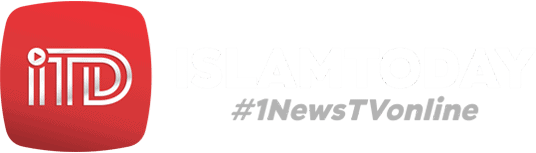(IslamToday ID) – Seiring kebencian anti-Muslim menyebar lintas benua, para ahli memperingatkan bahwa Islamofobia, manifestasi modern dari rasisme, bukan hanya masalah umat Muslim tetapi krisis yang mengancam fondasi demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme.
Para pakar internasional pada Minggu (13/4/2025) menyerukan tindakan global mendesak terhadap fenomena yang mereka gambarkan sebagai memburuk dengan cepat – pada sesi bertajuk ‘Menghadapi Diskriminasi dan Rasisme di Abad ke-21’ pada hari terakhir Forum Diplomasi Antalya keempat di kota resor Turki di Laut Tengah.
“Semakin kita mengejar masyarakat inklusif, semakin diskriminasi itu memanifestasikan dirinya,” kata Evren Dagdelen Akgun, Perwakilan Khusus untuk Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi Terhadap Muslim, Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE).
Mengutip data dari Badan Hak-Hak Fundamental Uni Eropa, ia menyoroti bahwa satu dari dua Muslim di Eropa menghadapi diskriminasi setiap hari, jika bukan pelecehan.
“Mengobati gejalanya tidak akan membawa kita pada masyarakat yang kohesif,” ia memperingatkan. “Kebencian anti-Muslim itu nyata, dan dengan nama apa pun kita menyebutnya, itu adalah bentuk rasisme.”
Akgun menunjuk pada lingkaran setan di mana rasisme dan Islamofobia menyusup ke dalam institusi demokrasi, mengikis representasi, kebebasan, dan kesetaraan. Pencabutan hak ini, pada gilirannya, merusak legitimasi demokrasi itu sendiri, sehingga lebih sulit untuk melawan tren ini secara efektif.
“Jika ditambah dengan retorika yang melanggengkan dan menormalisasi kebencian, impunitas akan terus menerus menjebak kita dalam lingkaran wacana dan tindakan anti-Muslim,” catatnya.
‘Bukan Hanya Masalah Muslim; Ini Masalah Hak Asasi Manusia’
Duta Besar Mehmet Pacaci, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Memerangi Islamofobia, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menggambarkan gambaran global krisis tersebut.
“Meskipun langkah signifikan telah dibuat melalui gerakan hak asasi manusia dan reformasi hukum, rasisme dan diskriminasi terus memanifestasikan diri dalam bentuk yang berkembang,” katanya. Ia menggambarkan rasisme modern sebagai “tertanam dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial.”
Pacaci mencantumkan statistik yang mengerikan: di Amerika Serikat, hampir 9.000 keluhan bias anti-Muslim tercatat pada tahun 2024—tertinggi sejak 1996. Di Eropa, insiden Islamofobia melonjak 43 persen tahun lalu, sementara di Australia dan Timur Jauh, pelecehan telah berlipat ganda dalam dua tahun terakhir, secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan anak perempuan.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik,” kata Pacaci. “Mereka mewakili orang-orang nyata, ibu, ayah, dan anak-anak yang hidup dalam ketakutan hanya karena keyakinan mereka.”
Ia mengkritik media arus utama karena memperkuat narasi dan teori konspirasi Islamofobia, sehingga menyusup ke dalam wacana publik dan pembuatan kebijakan.
“Normalisasi kebencian ini memiliki konsekuensi yang mengerikan,” ia memperingatkan. “Ini mengikis kohesi sosial, prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme… Rasisme anti-Muslim bukan hanya masalah Muslim; ini adalah masalah hak asasi manusia.”
Rasisme di Eropa Merajalela
Marion Lalisse, koordinator Uni Eropa untuk memerangi kebencian anti-Muslim di Komisi Eropa, menggemakan sentimen ini.
“Demokrasi, hak-hak fundamental, supremasi hukum—terlalu sering dianggap remeh,” katanya. “Menjadi demokrasi bukanlah label yang Anda dapatkan secara cuma-cuma. Itu adalah label yang Anda menangkan setiap hari.”
Ia menekankan bahwa rasisme di Eropa merajalela, menargetkan tidak hanya Muslim tetapi juga orang kulit hitam, Roma, Asia, dan Yahudi. “Roma seringkali menjadi kelompok yang paling dibenci dalam masyarakat kita,” katanya, mencatat bahwa meskipun perjuangan mereka, mereka adalah bagian tak terpisahkan dari identitas Eropa.
Lalisse menggarisbawahi pentingnya mengakui rasisme struktural, bukan hanya diskriminasi antar pribadi. “Rasisme telah berevolusi dari pertimbangan etnis menjadi budaya dan agama,” catatnya, menyatakan keprihatinannya terhadap Muslim di seluruh dunia, termasuk di India, China, Myanmar, AS, Kanada, Australia, dan Eropa.
Lalisse juga membahas tantangan yang dihadapi Komisi Eropa dalam menyeimbangkan tujuan anti-diskriminasi dengan kedaulatan nasional. Sementara negara-negara anggota mempertahankan kekuasaan utama, ia menekankan bahwa peran UE adalah untuk mendukung—bukan mengontrol—upaya mereka.
Ia juga menyinggung meningkatnya kebencian dalam politik dan media. Kekhawatiran utama, catat Lalisse, adalah peran media dalam menyebarkan stereotip berbahaya tentang Muslim dan migran.
“Jelas, Anda memiliki media yang melakukan pekerjaan dengan baik dalam mendokumentasikan kebencian, dan khususnya kebencian atau rasisme anti-Muslim, tetapi Anda memiliki yang lain yang bermain karena mereka tahu Anda dapat menghasilkan uang darinya, dan Anda dapat meliput Muslim di bawah sudut pandang spesifik terorisme dan migrasi, yang… menyebabkan ketegangan sosial,” jelasnya.
Untuk memerangi hal ini, UE bekerja sama dengan jurnalis, dewan etik, dan dewan pers untuk meningkatkan kesadaran. Lalisse menyoroti kemitraan yang didukung UE seperti Koalisi Eropa Kota-Kota Melawan Rasisme, yang mencakup Istanbul dan Antalya, sebagai jalan yang menjanjikan untuk perubahan akar rumput.
Demokrasi Liberal Tak Kebal Rasisme
Salman Sayyid, seorang profesor di Universitas Leeds dan suara akademis terkemuka tentang teori ras dan pascakolonial, menawarkan perspektif filosofis namun tajam.
“Islamofobia bukanlah masalah Barat. Ini masalah dunia,” katanya.
Ia berpendapat bahwa meskipun demokrasi dan liberalisme sering dirayakan sebagai cita-cita progresif, keduanya “sepenuhnya dan sama sekali kompatibel dengan rasisme,” yang membuatnya penting untuk secara aktif membentuk sistem ini menjadi kerangka kerja yang benar-benar anti-rasis dan anti-Islamofobia.
Sayyid menyoroti paradoks kunci rasisme modern: “Tidak ada yang mau disebut rasis, tetapi mereka tidak keberatan melakukan rasisme,” menunjuk pada bagaimana aktor politik sering membuat pernyataan besar tentang inklusi sambil memberlakukan atau memungkinkan praktik diskriminatif.
Ia menekankan bahwa Islamofobia bukan sekadar prasangka budaya atau bias individu, tetapi “hasil politik dari strategi politik,” yang digunakan sebagai alat untuk mendefinisikan kembali kontrak sosial antara penguasa dan yang diperintah.
“Islamofobia adalah cara kontrak antara penguasa dan yang diperintah sedang ditulis ulang,” catatnya, menambahkan bahwa itu telah bertransformasi menjadi wadah yang dapat diterima secara sosial di mana semua bentuk rasisme sekarang dapat disalurkan.
Sayyid juga memperingatkan bahwa Islamofobia mempengaruhi lebih dari sekadar Muslim—dampaknya meluas, seperti yang terlihat dalam kebijakan seperti larangan perjalanan Trump yang awalnya menargetkan Muslim tetapi akhirnya mempengaruhi orang lain, seperti “ilmuwan Prancis yang bukan Muslim.”
Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa perjuangan melawan Islamofobia bukan hanya perjuangan untuk hak-hak minoritas tetapi “pertempuran untuk masa depan masyarakat yang adil dan kemungkinan masyarakat yang adil.”
‘Hantu Menghantui Eropa dan Dunia…’
Sener Akturk, profesor politik perbandingan di Universitas Koc, menawarkan wawasan kunci tentang akar sistemik Islamofobia dan kaitannya dengan representasi yang tidak setara. Ia memulai dengan memparafrasekan pepatah terkenal: “Hantu menghantui Eropa dan dunia – dan ini adalah hantu kesetaraan dan representasi yang setara.”
Akturk berpendapat bahwa sebagian besar Islamofobia saat ini berasal dari perlawanan terhadap meningkatnya tuntutan akan kesetaraan nyata—tuntutan yang masih belum terpenuhi di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Ia mencatat bahwa populasi Muslim secara signifikan kurang terwakili dalam politik.
Di 26 negara Eropa, Muslim hanya memegang sepertiga kursi parlemen yang proporsional dengan populasi mereka.
Di Prancis, meskipun memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa, majelis nasional hanya memiliki segelintir anggota Muslim—jauh lebih sedikit dari 40 yang seharusnya mereka miliki di bawah representasi yang adil.
Lebih dari sekadar angka, Akturk menekankan masalah “representasi substantif” – banyak Muslim terpilih tidak benar-benar mewakili keprihatinan komunitas mereka.
Ia juga menantang pembagian “pribumi versus imigran” yang digunakan untuk meminggirkan Muslim, yang banyak di antaranya telah tinggal di Eropa selama beberapa generasi. Mengutip kehadiran Muslim bersejarah di Spanyol, Portugal, dan Sisilia, ia berpendapat bahwa membingkai Eropa sebagai “benua Kristen” menghapus masa lalunya yang kaya dan multi-religius.
Akturk menyimpulkan dengan mendesak perubahan dalam cara identitas dibahas. Masalah sebenarnya, katanya, bukanlah keturunan tetapi memastikan bahwa “semua orang, tanpa memandang agama atau warisan budaya, diperlakukan dengan martabat yang sama dan memiliki akses yang sama terhadap hak dan representasi.”
‘Multikulturalisme Itu Perlu’
Sebagian besar panelis setuju bahwa multikulturalisme menawarkan bukan hanya kerangka kerja untuk koeksistensi tetapi alat vital dalam memerangi Islamofobia, rasisme, dan diskriminasi.
Seperti yang ditunjukkan Sayyid, argumen untuk multikulturalisme seringkali hilang dalam iklim reaktif saat ini. “Kita perlu membuat argumen lagi mengapa penting bagi kita untuk menjadi multikultural,” katanya, menekankan bahwa multikulturalisme tidak hanya mulia tetapi juga perlu.
Dalam kata-katanya, “Kebaruan muncul dari kontak dengan keanehan, dan kita hanya menjadi lebih kreatif ketika kita menjumpai keragaman.”
Sementara itu, Akgun dari OSCE mencatat: “Istilah ‘multikulturalisme’ telah bersama kita sejak lama… ia akan tetap ada.”
Bersama-sama, perspektif ini memperkuat bahwa merangkul multikulturalisme bukan hanya cita-cita sosial tetapi keharusan strategis dan budaya dalam membangun masyarakat yang lebih adil, aman, dan dinamis.
Percakapan di Antalya menawarkan peta jalan ke depan: mengakui kebencian anti-Muslim sebagai rasisme; meminta pertanggungjawaban media dan aktor politik atas ujaran kebencian; mendukung inisiatif akar rumput untuk membangun masyarakat inklusif; dan memperjuangkan multikulturalisme bukan sebagai ancaman tetapi sebagai solusi.
Seperti yang disimpulkan Pacaci: “Ini adalah tantangan yang mengancam martabat dan keamanan semua kelompok yang terpinggirkan. Kita harus bertindak, bukan hanya untuk Muslim—tetapi untuk seluruh umat manusia.”