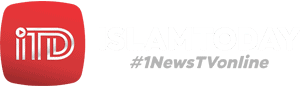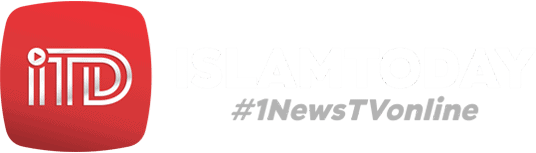(IslamToday ID) – Pakar politik Timur Tengah, Soumaya Ghannoushi, mengatakan pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada hari Selasa (29/4/2025) Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang menyatakan bahwa pertempuran tidak akan berakhir sampai ratusan ribu warga Gaza pergi dan Suriah dipisahkan, berhasil menepis kepura-puraan yang tersisa.
Menyebut perang Israel bukanlah tentang keamanan atau terorisme, tetapi tentang menggambar ulang peta itu sendiri, menghancurkan negara-negara, menggusur penduduk, dan menulis ulang sejarah.
Pada awal April, pesawat tempur Israel sekali lagi menyerbu langit Suriah, melepaskan rentetan rudal ke lokasi militer dan pemukiman warga sipil.
Serangan itu menyapu dari pangkalan udara pusat hingga ke selatan, tempat pasukan darat Israel membuat sayatan di dekat kota Nawa, menewaskan sembilan warga sipil.
Narasi resmi Israel, seperti biasa, berbicara tentang pertahanan dan pencegahan. Namun kebenarannya, yang sarat makna, lebih dalam dari sekadar geografi atau politik, itu adalah serangan ke dalam ingatan itu sendiri, kata Ghannoushi, dikutip dari Middle East Eye (MEE), Rabu (30/4/2025).
Karena dengan menyerang Nawa, Israel tidak hanya menyerang sebuah kota. Israel juga melanggar tempat suci warisan dan sejarah intelektual Muslim. Nawa adalah tempat kelahiran Imam al-Nawawi, salah satu ulama paling dihormati dalam peradaban Islam, yang karyanya bergema lintas abad dan benua, sambungnya.
Di sanalah Imam al-Nawawi menghafal Al-Quran, meninggalkan hiruk pikuk perdagangan dan mencari ketenangan dalam menuntut ilmu. Namanya masih dikenang dengan penuh penghormatan di rumah-rumah, sekolah-sekolah, dan mimbar-mimbar dari Kairo hingga Kuala Lumpur. Mengebom kota ini berarti mengebom garis keturunan yang penuh kebijaksanaan.
Tidak jauh dari Nawa berdirilah Tell al-Jabiyah, tempat Khalifah Omar ibn al-Khattab pernah berdiri, setelah melakukan perjalanan dari Madinah untuk menerima kunci Yerusalem. Di sana, di bukit kuno itu, ia bertemu dengan para komandannya beberapa jam sebelum serah terima bersejarah. Jejak langkah mereka masih bergema di tanah Houran. Itu adalah tanah suci, disucikan bukan hanya oleh iman, tetapi juga oleh beban sejarah.
Di sebelah selatan dan timur terdapat tanah kelahiran para pemikir terkemuka lainnya. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, ahli hukum dan teolog besar, berasal dari kota Izraa di Daraa. Ibn Kathir , sejarawan terkenal Al-Bidaya wal-Nihaya, lahir di desa Majdal dekat Bosra.
Wilayah ini, Houran, telah lama menjadi sumber ilmu pengetahuan, tanahnya menyuburkan peradaban yang melampaui batas wilayah, sekte, dan kekaisaran.
Dan di sinilah pula, di tepi Sungai Yarmouk, Khalid ibn al-Walid memimpin pasukan Muslim pada tahun 636 M menuju kemenangan penting melawan Bizantium – menghancurkan kekuasaan kekaisaran dan membuka babak baru dalam sejarah dunia, tutur Ghannoushi.
Berperang di tanah ini bukan sekadar melanggar kedaulatan. Itu sama saja dengan menantang hakikat keberlangsungan Arab dan Islam. Tanah Houran bukanlah medan pasif, tanah ini adalah saksi dari perlawanan, penaklukan, dan kebangkitan selama berabad-abad.
Serangan Israel, oleh karena itu, tidak hanya bersifat fisik tetapi juga simbolis. Serangan itu bukan hanya tentang dominasi militer. Serangan itu tentang penghapusan.
Sejak jatuhnya rezim Assad pada 8 Desember 2024, Israel telah melancarkan operasi paling gencarnya di wilayah Suriah dalam beberapa tahun terakhir. Ratusan serangan udara telah menghancurkan infrastruktur militer, sistem pertahanan udara, dan depot senjata.
Pembenaran yang diberikan sederhana, Israel tidak mempercayai pemerintahan transisi yang baru. Namun, cakupan dan waktu serangan menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Hanya satu hari setelah Assad melarikan diri ke Moskow, para pemimpin Israel menyatakan niat mereka untuk membentuk zona keamanan steril di dalam wilayah Suriah, yang membentang sekitar 400 kilometer persegi, lebih luas dari seluruh wilayah Jalur Gaza.
Pasukan Israel kini telah mengambil posisi di sepanjang sisi Gunung Hermon di Suriah, yang secara terbuka menentang hukum internasional. Dan meskipun para pejabat awalnya mengisyaratkan pendudukan sementara, mereka kemudian telah membuka kedoknya.
Tidak ada batas waktu. Tidak ada rencana keluar.
“Kami akan tetap bertahan”, tegas Menteri Pertahanan Israel Katz, yang berdiri di puncak gunung.
“Kami akan memastikan bahwa seluruh zona selatan didemiliterisasi, dan kami tidak akan menoleransi ancaman terhadap komunitas Druze.”
Maka dimulailah pertunjukan berupa seruan untuk melindungi kaum minoritas. Israel mengklaim melindungi kaum Druze dari ancaman yang dibayangkan oleh pemimpin baru Suriah. Namun sejarah menunjukkan kepalsuan klaim tersebut.
Kaum Druze di Palestina, yang telah lama menjadi anggota tentara Israel, telah berjuang demi negara yang mereka harapkan akan memperlakukan mereka setara. Mereka adalah kaum Druze dari Galilea, yang secara resmi menjadi warga negara Israel, yang menjawab panggilan negara untuk mengabdi tetapi kemudian mendapati diri mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di tanah air mereka sendiri.
Namun, pengkhianatan itu terjadi secara sistematis. Diskriminasi dalam bidang perumahan, pendidikan, kepemilikan tanah, dan pengakuan politik sangat dalam. Sebuah laporan tahun 2024 oleh lembaga pemikir terkemuka Israel, Institut Studi Keamanan Nasional (INSS), memperingatkan, “Jika Israel terus mengabaikan masalah yang dihadapi komunitas Druze, para anggotanya akan merasa ditinggalkan, yang berpotensi membahayakan hubungan mereka dengan negara.”
Disahkannya Undang-Undang Negara Bangsa tahun 2018, yang mengukuhkan Israel sebagai negara Yahudi dan merendahkan derajat orang non-Yahudi secara permanen, merupakan titik balik bagi banyak orang. Perjanjian darah, yang dulu digembar-gemborkan dengan bangga, telah menjadi batu nisan yang pahit.
Rumah-rumah Druze terancam dibongkar. Protes Druze memenuhi jalan-jalan. Namun, Israel tetap menampilkan diri sebagai penyelamat mereka di Suriah meskipun gagal di tanah air mereka sendiri. Hal yang sama berlaku bagi suku Badui, warga negara Arab yang bertugas di tentara pendudukan Israel, hanya untuk kembali ke desa-desa yang dianggap ilegal, rumah-rumah mereka ditandai untuk dihancurkan.
Ini bukan perlindungan. Ini eksploitasi, yang dibungkus dengan bahasa keprihatinan, sebut Ghannoushi.
Sebenarnya, ambisi Israel jauh melampaui batas wilayah atau kaum minoritas. Visinya untuk Suriah adalah fragmentasi permanen.
Hanya sehari setelah Assad melarikan diri, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar dengan gamblang menyatakan bahwa Suriah seharusnya tidak lagi menjadi negara kesatuan. Ia menyerukan zona otonomi – kanton untuk setiap komunitas.
“Ide Suriah yang berdaulat tunggal tidak realistis,” katanya.
Lebih jelasnya, pengacara Israel dan dosen militer Rami Simani menyatakan, “Suriah adalah negara buatan yang telah hancur. Negara itu tidak pernah memiliki hak nyata untuk eksis. Negara itu bukan negara Arab, dan tentu saja bukan negara-bangsa siapa pun Erdogan mendukung Suriah yang bersatu. Kepentingan Israel sepenuhnya bertolak belakang. Israel dapat dan harus menyebabkan Suriah menghilang. Sebagai gantinya akan ada lima kanton Israel harus memperdalam cengkeramannya di wilayah pedalaman Suriah.”
Ini bukan sekadar retorika. Ini adalah kebijakan.
Israel membayangkan Suriah yang terpecah-pecah: wilayah Kurdi di timur laut, protektorat Druze di selatan, kantong Alawite yang memeluk pantai, dan wilayah-wilayah Sunni yang tersebar yang dilucuti kedaulatannya.
Tujuannya bukanlah perdamaian, melainkan kelumpuhan.
Suriah yang hancur tidak dapat menahan pendudukan atas tanahnya. Suriah yang terpecah tidak dapat berbicara atas nama Palestina .
Suriah yang terfederalisasi tidak dapat memimpikan kemerdekaan. Jadi, dengan dalih keamanan, Israel memperdalam jejaknya. Namun pandangannya diarahkan ke luar Suriah, ke Turki.
Meskipun Ankara telah berulang kali berjanji untuk menghindari konfrontasi, ahli strategi Israel sekarang menganggapnya sebagai ancaman yang lebih besar daripada Iran.
Turki mendukung Suriah yang bersatu. Israel mendukung pembubarannya.
Serangan awal April, termasuk yang terjadi di dekat Nawa, membawa sebuah pesan yang tidak hanya kepada Damaskus, tetapi juga kepada Ankara, “Ini adalah wilayah pengaruh kami.”
Keheningan dari Damaskus cukup menonjol. Kepemimpinan baru Suriah, yang masih belum stabil, hanya mengeluarkan tanggapan yang hati-hati. Beberapa pejabat bahkan melontarkan gagasan perdamaian.
“Kami berkomitmen pada perjanjian 1974,” kata presiden baru Suriah, Ahmed al-Sharaa, “Dan tidak akan membiarkan wilayah Suriah digunakan untuk serangan.”
Dalam pernyataan lebih lanjut, Sharaa dilaporkan mengatakan kepada seorang anggota parlemen AS bahwa Suriah siap untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan bergabung dengan Perjanjian Abraham di bawah kondisi yang tepat, dengan mengupayakan keringanan sanksi dan penyelesaian atas pendudukan Israel di Suriah barat daya. Sharaa kemudian membantah bahwa Suriah dapat menormalisasi hubungan dengan Israel selama negara itu masih diduduki.
Namun, tindakan ini tidak disambut dengan diplomasi, tetapi dengan lebih banyak bom dan dengan deklarasi yang menghapus segala kepura-puraan kompromi.
Dalam pidatonya kepada kadet militer Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Israel tidak akan mengizinkan pasukan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) atau tentara Suriah baru untuk memasuki wilayah selatan Damaskus.
Ia menuntut demiliterisasi penuh provinsi Quneitra, Daraa, dan Sweida, dan memperingatkan bahwa Israel tidak akan menoleransi ancaman apa pun terhadap komunitas Druze di Suriah selatan.
Posisi Israel tidak salah lagi: tidak ada ruang bagi kedaulatan Suriah.
Di Washington, Israel melobi agar sanksi diperketat. Para pejabat AS kini mengajukan daftar tuntutan yang mustahil kepada Damaskus di antaranya, pelarangan semua aktivitas politik Palestina di tanah Suriah.
Suatu bangsa yang terhuyung-huyung karena perang selama 14 tahun diberitahu bahwa mereka harus mengorbankan tidak hanya kemerdekaannya, tetapi juga aliansinya, ingatannya, suaranya.
Namun ada sesuatu yang terjadi di Suriah.
Upacara pemakaman sembilan orang yang terbunuh di Nawa menjadi prosesi perlawanan. Di seluruh negeri, warga Suriah turun ke jalan.
Kelelahan akibat perang mulai berganti menjadi tekad baru. Generasi yang pernah kehilangan harapan kini menemukannya lagi bukan pada pemerintah, tetapi pada tanah air itu sendiri.
Karena Suriah bukan sekadar negara, ia adalah peradaban. Ia adalah tempat lahirnya kekaisaran, kuburan para penjajah. Ia bertahan dari Perang Salib, mengusir kolonialisme, dan bangkit melawan tirani.
Lukanya banyak, tetapi jiwanya bertahan. Musuh mungkin kuat. Namun negeri ini mengingatnya.
Strategi Israel, dengan segala perhitungannya, dibangun di atas ilusi yang fatal: bahwa suatu negara dapat dihapus dengan menggambar ulang peta dan menjatuhkan bom. Namun Suriah bukan hanya sekadar wilayah. Suriah adalah Nawa dan Yarmouk, Ibn Kathir dan Saladin, Sultan Pasha al-Atrash dan Khalid ibn al-Walid.
Sejarah telah menjadi kenyataan, martabat terukir di tanah. Suriah tidak akan lenyap. Suriah tidak akan terpecah belah secara diam-diam. Dan rakyatnya, meskipun babak belur, sedang bangkit.
Apa yang dilancarkan Israel di Suriah selatan bukanlah penyerahan, melainkan kenangan. Bagi warga Suriah dan Palestina, perjuangannya bersama, lukanya satu. Dan sejarah, saksi panjang kebangkitan dan kejatuhan kekaisaran tetap berada di pihak mereka, pungkasnya. [ran]