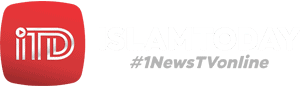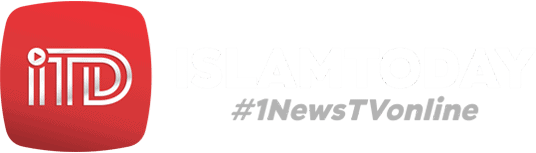(IslamToday ID) – Menteri Keuangan ekstremis negara pendudukan Bezalel Smotrich yang juga memegang jabatan di Kementerian Pertahanan – mengungkap ambisi kolonial maksimalis Tel Aviv. Laporan koresponden The Cradle untuk Palestina yang dikutip Selasa (6/5/2025), hal tersebut dikatakan Smotrich setelah berminggu-minggu menerima laporan tentang eksodus diam-diam warga Gaza ke Eropa sebagian melalui Bandara Ramon di selatan Palestina yang diduduki, sebagian lainnya melalui Bandara Ben Gurion di Tel Aviv.
Insiden terbaru, yang didokumentasikan dalam sebuah video yang beredar, menunjukkan Prancis sebagai tujuan mereka.
Yang menonjol adalah ambiguitas yang mencolok seputar evakuasi ini dan kebungkaman yang memekakkan telinga dari pemerintah-pemerintah Barat dan lembaga-lembaga internasional. Kebungkaman ini tampaknya disengaja memungkinkan Israel untuk mengeksploitasi narasi tersebut sambil menyelamatkan para pejabat dari ketidaknyamanan dalam menantang fantasi-fantasi deportasi Presiden AS Donald Trump yang tidak terkendali namun terus-menerus, kata koresponden itu.
Menurutnya, Pernyataan Smotrich dan gerakan rahasia yang kini tengah berlangsung dan muncul hampir 19 bulan setelah perang brutal Israel di Gaza. Pernyataan itu muncul setelah Israel berulang kali mengancam akan memindahkan penduduknya secara paksa. Namun, jika jalannya perang ini memperjelas sesuatu, maka tujuan utama negara pendudukan itu adalah pembunuhan massal dan kelaparan warga Palestina untuk mematahkan perlawanan mereka dan menyebarkan teror di kawasan itu. Jauh sebelum ada upaya pemindahan yang terorganisasi.
Terkait keberangkatan terbaru ke Prancis, The Cradle berbicara dengan sumber diplomatik Prancis yang mengetahui operasi tersebut. Mereka mengonfirmasi bahwa puluhan warga Palestina telah melakukan perjalanan ke Paris, tetapi bersikeras bahwa itu dilakukan berdasarkan program lama yang diluncurkan pada awal perang untuk pemegang paspor Prancis atau kerabat mereka yang tinggal di Gaza.
Namun, sumber-sumber tersebut mengakui bahwa program tersebut telah diperluas untuk mencakup para profesional berbahasa Prancis dan individu yang berafiliasi dengan Institut Kebudayaan Prancis di Gaza. Perluasan tersebut, menurut mereka, lebih mencerminkan penyesuaian logistik daripada agenda politik apa pun.
Mereka dengan tegas menolak klaim yang dibuat oleh kelompok hak asasi manusia, seperti Euro-Med Human Rights Monitor, bahwa Prancis memfasilitasi evakuasi yang lebih luas. Sumber tersebut menambahkan bahwa mereka secara pribadi mengawasi pemindahan warga negara Prancis dan kerabat dekat mereka, dan mengatakan kepada The Cradle , program tersebut ditangguhkan setelah Israel mengambil alih Rafah.
“Namun mengingat penentangan Eropa terhadap deportasi Palestina, Israel melihat peluang untuk membuka kembali program lama ini sebagai pintu gerbang untuk memperluasnya ke kelompok-kelompok baru,” kata sumber tersebut.
Yang berbeda kali ini adalah koordinasi melalui Ramallah, dengan melibatkan kedutaan Prancis dan Otoritas Palestina (PA). Namun, jumlah pengungsi masih sangat terbatas dan tidak termasuk kerabat tingkat kedua – meskipun beberapa akademisi dan seniman yang memiliki hubungan budaya dengan Prancis termasuk di antara mereka yang mengungsi.
Menurut sumber yang sama, yang terjadi justru sebaliknya, ada penolakan terhadap hukum atau perundang-undangan apa pun untuk menerima mereka yang melarikan diri dari perang.
Yang lebih menarik lagi adalah laporan Haaretz pada tanggal 15 April yang menyebutkan bahwa Prancis dan aktor internasional lainnya terlibat dalam pembicaraan dengan Mesir untuk menampung sementara para pengungsi selama fase rekonstruksi. Sebagai gantinya, Kairo akan menerima keringanan utang sebagian dan peran rekonstruksi yang lebih besar, yang secara efektif menghasilkan uang dari pengungsian sementara.
Jejak Prancis yang semakin besar dalam masalah Palestina telah mencapai titik tertinggi baru, dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mempelopori upaya untuk memperbarui kepemimpinan di Ramallah. Paris mengupayakan hal ini melalui dua jalur: menjadi sponsor bersama dengan Arab Saudi untuk konferensi perdamaian pada bulan Juni 2025 guna mendukung rencana rekonstruksi Gaza oleh Kairo, dan memberikan tekanan langsung kepada Presiden PA Mahmoud Abbas untuk menunjuk seorang wakil, sebuah langkah yang sudah berlangsung. Sebagai balasannya, Uni Eropa telah menjanjikan bantuan sebesar €1 miliar (sekitar $1,07 miliar) kepada PA selama dua tahun.
Sementara itu, Israel berupaya memasukkan jaminan ke dalam setiap kesepakatan di masa mendatang. Seperti yang dilaporkan oleh media Israel, Paris mengusulkan mekanisme pemantauan yang akan memungkinkan Israel untuk melaksanakan operasi militer yang diperlukan di Gaza pasca-penarikan, mirip dengan model AS-Prancis di Lebanon pascaperang.
Namun sumber-sumber diplomatik senior Mesir mengatakan kepada The Cradle bahwa Kairo telah menolak evakuasi warga negara ganda melalui penyeberangan Israel. Meskipun pergerakan ini terbatas, Mesir khawatir hal itu dapat menjadi preseden.
Pejabat itu melanjutkan dengan mencatat bahwa Mesir telah mendapatkan janji dari mitranya di Eropa untuk menentang migrasi sukarela dan paksa atau evakuasi besar-besaran di Gaza.
Beberapa sumber Palestina yang memiliki hubungan dengan ibu kota Eropa, bersama dengan pejabat Hamas yang memantau masalah tersebut, memberi tahu The Cradle tentang pola baru yang meresahkan, pemuda Palestina di Gaza yang tidak berafiliasi dengan perlawanan menyerahkan diri kepada pasukan pendudukan. Harapan mereka adalah penangkapan tersebut dapat memberikan makanan dan tempat tinggal sementara, atau bahkan deportasi.
Namun pasukan Israel sering kali menyimpang dari harapan ini. Jika tidak ditembak di tempat, para pemuda Palestina ini diinterogasi dan dikembalikan ke Gaza terkadang dengan tawaran untuk menjadi informan. Tidak ada protokol aktif untuk deportasi, dan tidak ada mekanisme operasional yang diketahui terkait dengan unit deportasi sukarela Israel yang baru-baru ini diumumkan. Jika skema semacam itu ada, para pemuda yang putus asa ini akan menjadi kasus uji pertamanya.
Menurut seorang pejabat senior Palestina, hanya sekitar 150 orang yang telah dievakuasi ke Prancis sejak gelombang pengungsian terakhir dimulai. Semua orang dievakuasi melalui penyeberangan Kerem Shalom berdasarkan koordinasi sebelumnya dengan pemerintah Eropa.
Mereka adalah orang-orang dengan beasiswa akademis dan budaya, kerabat tingkat pertama yang tinggal di Uni Eropa, atau pengungsi yang permintaannya tertunda akibat serangan Rafah, ungkap sumber tersebut.
Sementara itu, Jerman telah memulai evakuasi penuh staf GIZ (Badan Kerja Sama Internasional Jerman) di Gaza. Berlin menawarkan perumahan, tunjangan, pendidikan, dan kursus intensif bahasa Jerman kepada personel dan keluarga mereka totalnya sekitar 120 orang.
Belgia telah menerapkan operasi serupa tetapi dalam skala yang lebih kecil. Negara ini telah menyediakan pendidikan bahasa Prancis bagi karyawan lembaga dan memungkinkan sejumlah kecil warga Palestina untuk membawa satu atau dua kerabat tingkat pertama.
Australia, yang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Israel, juga telah menangani kasus-kasus individual yang melibatkan hubungan keluarga. Canberra dilaporkan sedang meninjau berbagai cara untuk memperpanjang masa tinggal warga Palestina dengan visa kunjungan yang akan segera berakhir, tetapi belum menjelaskan apakah akan menawarkan mereka status Safe Haven atau status perlindungan permanen.
Yang penting, tidak satu pun evakuasi ini melibatkan warga negara Mesir atau penduduk negara-negara Teluk Persia. Koordinasi terbatas pada negara-negara anggota UE dan beberapa mitra Barat terpilih.
Selektivitas geografis operasi ini memperlihatkan batas-batas sifat kemanusiaan yang seharusnya. Bahkan ketika penyeberangan Rafah beroperasi, warga negara Lebanon, penduduk Suriah, dan pengungsi Palestina dari Suriah dilarang menyeberang, meskipun ada lobi dari Beirut dan Damaskus. Kairo mengutip keberatan Israel untuk membenarkan penolakannya.
Kebijakan selektif ini merupakan hukuman kolektif, yang tidak hanya menargetkan warga Palestina tetapi juga semua negara yang dianggap tidak diinginkan secara politik di mata Tel Aviv.
Pertanyaan yang muncul adalah, Apakah ini uji coba untuk deportasi massal?
Para pemimpin faksi Palestina di Gaza dan Beirut yang berbicara dengan The Cradle mengakui kekhawatiran mereka yang masih ada tentang pemindahan internal dan pemukiman kembali eksternal. Namun, mereka juga mendeteksi adanya kemunduran yang jelas dari Washington – yang sudah memengaruhi sikap Israel.
Mereka menunjuk pada beberapa faktor, yakni perlawanan Palestina yang tak kenal kompromi, perlawanan Mesir yang tak kenal kompromi , dan – meskipun tidak konsisten – keraguan Yordania. Kekuatan-kekuatan ini secara kolektif telah menghalangi skema deportasi. Dibandingkan dengan tahun 1948, realitas demografi saat ini membuat pengulangan itu mustahil.
Bahkan jika warga Palestina direlokasi ke negara-negara Arab di dekatnya, hal itu tidak akan menyelesaikan apa pun. Kedekatan mereka dengan Palestina memastikan perlawanan baru. Jika proyek pemindahan harus dilanjutkan, maka warga Palestina harus dikirim jauh ke luar wilayah tersebut bukan ke negara-negara Eropa yang pada akhirnya dapat memberi mereka kewarganegaraan, yang memungkinkan mereka kembali secara sah ke Israel sendiri.
Sejarah terkini memberikan contoh kasus yang jelas. Meskipun operasi militer gencar dilakukan, Israel tidak berani mengusir penduduk kamp pengungsi Jenin, Tulkarm, atau Nour Shams ke luar desa-desa terdekat. Israel juga tidak mendorong mereka ke Lembah Yordan atau bahkan kota-kota di Tepi Barat bagian tengah.
Sebaliknya, Tel Aviv menggambarkan pemindahan ini sebagai sementara hingga kamp-kamp tersebut dibersihkan sambil secara efektif menghancurkannya.
Hal ini bukan karena kurangnya kapasitas militer atau ketakutan terhadap Yordania. Israel tahu bahwa kondisi untuk pemindahan massal secara paksa belum matang.
Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, Palestina tidak menyerah. Sebaliknya, penolakan mereka untuk menyerah meskipun kalah dalam persenjataan terlihat jelas. Setiap penerapan pemindahan paksa di Gaza atau Tepi Barat dapat memicu satu hal yang paling ditakuti Israel, pemberontakan rakyat yang meluas.
Ada satu detail terakhir yang krusial. Hampir 100.000 warga Palestina melarikan diri ke Mesir selama perang. Gelombang terbaru masuk setelah pendudukan Israel di Rafah pada Mei 2024. Orang-orang ini kini telah tinggal di Mesir selama satu setengah tahun. Namun Kairo belum memberi mereka izin tinggal, atau memfasilitasi perjalanan ke negara ketiga dengan mengizinkan pengajuan visa melalui kedutaan besar di sekitarnya.
Mereka tetap berada dalam ketidakpastian birokrasi dan eksistensial, menanti rekonstruksi dan pembukaan kembali Rafah, bertahan hidup dengan kebutuhan minimum.
Mengapa Kairo tidak mengintegrasikan mereka atau mendeportasi mereka?
Seorang sumber keamanan senior Mesir memberi tahu The Cradle bahwa Kairo sengaja berpegang pada kartu Gaza. Tidak seperti penerimaan yang lebih diam-diam terhadap arus pengungsi dari Sudan, Suriah, dan Libya yang sebagian besar masih tanpa status hukum atau dukungan publik, Mesir secara aktif membuat warga Palestina di Gaza berada dalam ketidakpastian birokrasi.
Sebaliknya, Mesir lebih suka menggunakannya sebagai pengaruh untuk menekan barat agar membuka Rafah dan mempertahankan krisis kemanusiaan yang dapat dijadikan senjata.
Kebijakan ini, meskipun secara taktis baik bagi Kairo, sangat merugikan bagi para pengungsi. Kebijakan ini merendahkan martabat mereka dan menghalangi masa depan mereka dan anak-anak mereka. [ran]