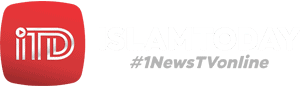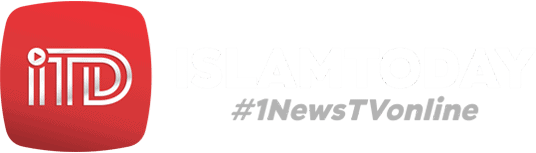(IslamToday ID) – Presiden Rusia Vladimir Putin mengejutkan dunia dengan mengusulkan dimulainya kembali negosiasi terkait perang proxy di Ukraina yang sempat dibatalkan tiga tahun lalu di Istanbul. Namun, apakah langkah ini benar-benar mengubah peta permainan geopolitik? Jawabannya bergantung pada perspektif mana yang digunakan.
Putin tidak hadir langsung di Istanbul untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Sebagai gantinya, Rusia diwakili oleh Vladimir Medinsky, sejarawan terkemuka yang juga memimpin delegasi dalam negosiasi awal tahun 2022. Eropa tampaknya tersingkir dari pembicaraan ini, hanya berperan lewat pengarahan sebelumnya terhadap delegasi Ukraina. Sementara itu, negara-negara Eropa Barat justru sibuk menyerukan sanksi tambahan terhadap Rusia.
Pada Maret 2022, sebenarnya Kiev memiliki kesempatan menghentikan perang. Namun, kesepakatan yang sempat dicapai itu gagal diimplementasikan. Kini, Ukraina menghadapi situasi yang jauh lebih buruk: lebih dari satu juta korban jiwa, kehilangan wilayah, sumber daya alam dikuasai asing, dan ekonomi yang runtuh.
Dalam pembicaraan terbaru di Istanbul, Medinsky menegaskan kesiapan Rusia menghadapi konflik jangka panjang. Ia mengutip sejarah perang Rusia-Swedia selama 21 tahun sebagai bukti ketahanan negaranya. Pesan yang disampaikan jelas: menyerah atau hadapi konsekuensi lebih besar.
Pertemuan di Istanbul kali ini lebih bernuansa diplomasi simbolis daripada substansi. Pemerintah Turki di bawah Presiden Erdogan menjadi tuan rumah, namun pertemuan tersebut tampak lebih seperti strategi pencitraan Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyampaikan hasil nyata seperti pertukaran 1.000 tahanan dari masing-masing pihak dan pembahasan kemungkinan gencatan senjata.
Namun, banyak pihak menilai negosiasi ini masih jauh dari menyentuh akar persoalan utama: keseimbangan strategis kawasan Eropa Timur dari Laut Barents hingga Laut Hitam. Tanpa kesepakatan keamanan yang menyeluruh, konflik akan terus berlanjut.
Bahkan analis militer Barat mulai mengakui bahwa Rusia kini berada di atas angin. Sementara itu, negara-negara Eropa tampak tidak realistis dengan terus berharap pihak yang kalah dapat menentukan syarat gencatan senjata.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengungkapkan bahwa pada April 2022 telah dicapai kesepakatan antara Rusia dan Ukraina. Namun, karena tidak pernah ditepati, wilayah Ukraina terus menyusut. Hal ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran perjanjian hanya memperparah posisi Kiev.
Kekalahan Ukraina berarti juga kekalahan NATO dan Amerika Serikat, sesuatu yang tak bisa diterima oleh elit politik Washington. Sebab itu berarti kehilangan kendali atas Eurasia—mimpi buruk bagi para arsitek geopolitik seperti Mackinder dan Brzezinski. Kini, dunia menyaksikan konsolidasi tatanan multipolar yang dipimpin kemitraan strategis Rusia-Tiongkok.
Bagi Beijing, Ukraina hanyalah batu loncatan NATO untuk menyerang Rusia sebelum akhirnya menghadapi Tiongkok dari dua arah: darat dan laut. Oleh karena itu, kendali atas Taiwan menjadi kepentingan strategis bagi Beijing. Dalam konteks ini, Tiongkok dan Rusia dinilai mampu mengalahkan NATO dalam skenario perang multipolar.
Zelenskyy sendiri dinilai tidak memiliki kuasa nyata dalam negosiasi. Ia hanya menjadi wajah dari kelompok ekstremis yang mengendalikan Ukraina dari balik layar. Dukungan penuh dari Inggris, Prancis, dan Jerman justru membuatnya semakin terobsesi melanjutkan perang yang menghancurkan negaranya sendiri.[sya]