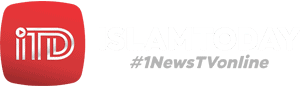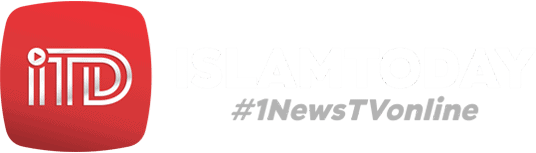(IslamToday ID) – Peringatan 27 tahun Reformasi diwarnai oleh erosi hak asasi manusia, melalui pengabaian pelanggaran HAM masa lalu dan pengulangannya di masa kini, akibat kebijakan dan praktik otoriter yang melemahkan kebebasan sipil, politik dan keadilan sosial.
“Ketika hukum dan praktik otoriter berkembang biak demi kepentingan segelintir orang, negara dan masyarakat sipil harus segera bekerja sama untuk melindungi kembali hak asasi sebagai amanat reformasi. Putusan terbaru Mahkamah Konstitusi adalah modalitas tersisa,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu (21/5/2025).
Erosi Kebebasan Politik & HAM di Indonesia
Usman mengungkapkan, indikator-indikator internasional yang kredibel, menunjukkan erosi kebebasan dan hak asasi manusia di Indonesia.
Freedom House mencatat penurunan tajam dalam kebebasan sipil dan hak politik, di mana indeks demokrasi Indonesia turun dari skor 62 pada 2019 menjadi 57 pada 2024.
Kemudian, World Press Freedom Index 2025 pada 3 Mei lalu mencatat, indeks kebebasan pers di Indonesia kian merosot hingga ke posisi 127 dari 180 negara.
Sementara, Economist Intelligence Unit (EIU) juga masih menilai Indonesia sebagai ‘demokrasi cacat’.
Dan laporan terbaru V-Dem Institute mencatat, Indonesia tergelincir dari status demokrasi elektoral menjadi otokrasi elektoral.
Menurutnya, kemerosotan itu terjadi karena Indonesia menjauhi cita-cita reformasi dengan melemahnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, otonomi daerah, hingga jaminan kebebasan sipil maupun pers.
“Jangankan Tragedi 1965/1966 atau Tragedi Tanjung Priok 1984, penembakan mahasiswa Trisakti, pembakaran anak-anak miskin kota dan pemerkosaan masal Mei 1998 yang tidak terlalu lama saja luput dari supremasi hukum. Ini tragedi luar biasa yang dilupakan. Alih-alih ada keadilan korban, fakta tragedi ini justru terancam hilang oleh kebijakan penulisan ulang sejarah,” ungkapnya.
Erosi kebebasan politik, kata dia, juga terlihat pada kasus-kasus serangan terhadap kebebasan sipil maupun pers.
Kasus terakhir, aparat menangkap mahasiswi seni rupa ITB yang membuat meme Presiden dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah.
Kebebasan berkesenian juga terancam seperti dialami pelukis Yos Soeprapto di Jakarta, teater “Wawancara dengan Mulyono” di Bandung dan band Sukatani dari Purbalingga belum lama ini.
530 Kriminalisasi Terjadi Sepanjang 2019–2024
Amnesty International Indonesia mencatat, selama 2019–2024 setidaknya terdapat 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi dengan jerat UU ITE terhadap 563 korban.
Pelaku didominasi oleh patroli siber Polri (258 kasus dengan 271 korban) dan laporan Pemerintah Daerah (63 kasus dengan 68 korban).
Terakhir, lanjut Usman, aparat menangkap mahasiswa Universitas Diponegoro dengan pasal “penyekapan” saat Aksi MayDay.
Di area legislasi, KUHP baru masih berpotensi membungkam kritik, termasuk pasal anti makar.
Antara lain, penodaan agama, penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat dan institusi negara.
Ia menilai, Rencana revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Polri juga lebih terlihat seperti perebutan wewenang antara kepolisian dan kejaksaan, tanpa mementingkan jaminan hak asasi manusia.
“KUHP baru itu perlu direvisi kembali. Apalagi usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sejumlah putusan penting pada April lalu. Salah satunya, mengecualikan institusi pemerintah, korporasi, profesi, dan jabatan dari pihak yang dapat melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Ini modalitas positif yang membawa harapan,” jelas Usman.
Selain merosotnya indeks kebebasan pers, Amnesty bersama Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), juga mencatat kasus-kasus intimidasi dan kekerasan pada jurnalis.
Pasalnya, RUU Penyiaran juga berpotensi membungkam kritik media terutama jurnalisme investigatif.
Usman menuturkan, sepanjang lima bulan sejak Januari–Mei tahun ini saja, setidaknya telah terdapat 29 jurnalis yang menjadi target serangan.
Erosi Hak-hak Sosial
Erosi hak-hak sosial, ucap Usman, terlihat dalam pelanggaran HAM baru yang dipicu oleh pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Kemudian, ihwal investasi, dan stabilitas politik keamanan seolah seperti era otoriter.
Dari Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, hingga Jawa, Amnesty terus menerima laporan kredibel terkait berbagai kasus.
Semisal, perampasan tanah adat, intimidasi, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan tidak satu pun diselesaikan secara adil.
“Tokoh-tokoh adat seperti Sorbatua Siallagan di Sumatera Utara atau masyarakat adat biasa seperti di Halmahera Timur mengalami intimidasi dan kriminalisasi atas tuduhan tak berdasar. Jika negara tak mau membela hak masyarakatnya sendiri, ke mana lagi mereka berlindung?” tanya Usman.
Atas kejadian tersebut, di Indonesia bukan hanya terjadi kemunduran dalam kebebasan politik.
Tetapi, juga dalam keadilan sosial yang terlihat dari ketimpangan distribusi sumber ekonomi.
Antara lain: akibat kasus-kasus perampasan lahan, perusakan lingkungan dan eksploitasi sumber alam.
Keprihatinan Amnesty, juga beranjak dari data-data resmi Pemerintah, yang mencerminkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia kian melebar.
Data BPS, sebagai contoh, jelas menunjukkan bahwa koefisien gini naik dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,381 pada September 2024.
“Ini menandakan jurang antara si kaya dan si miskin makin besar,” ucap Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia.
Kemunduran Supremasi Sipil
Sementara itu, Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia Wirya Adiwena, menambahkan, bahwa salah satu penyebab terjadinya erosi kebebasan politik dan hak sosial itu adalah mundurnya supremasi sipil.
“Revisi UU TNI yang memperluas peran militer dalam urusan sipil bahkan mengarah pada melemahnya supremasi sipil dan pelanggaran hak asasi manusia. Contoh, militer mulai melakukan pengawasan kegiatan mahasiswa dengan dalih ‘monitoring wilayah’ seperti kasus UIN Walisongo di Semarang, Universitas Indonesia di Depok, dan Universitas Udayana di Bali,” tutur Wirya.
Wirya mengatakan, bahwa kampus adalah tempat kebebasan berpikir kritis, berdialog, dan menumbuhkan keberagaman gagasan.
“Kehadiran militer, apalagi tanpa dasar hukum yang jelas, dapat menciptakan iklim ketakutan, sensor diri, dan pembungkaman ekspresi kritis. Itu adalah praktik otoriter era dulu,” imbuhnya.
Selanjutnya, sebut Wirya, pelibatan TNI Angkatan Darat dalam penegakan hukum dan pengamanan kejaksaan di seluruh Indonesia.
Yakni, juga menunjukkan kesan Indonesia bukan negara yang demokratis, di mana supremasi sipil dan independensi peradilan terjamin.
Rezim otoriter, sebut Wirya, memang sudah mati 27 tahun lalu, tapi warisan otoriter dapat hidup dalam kebijakan dan praktik negara.
“Pemimpin otoriter masa lalu gagal diadili, jangan sampai kini dijadikan pahlawan nasional dan sejarah kekejamannya dihapuskan dari ingatan kolektif,” tambah Wirya.
Sekalipun berat, Amnesty melihat harapan menyelamatkan Reformasi ke marwahnya masih tinggi.
Di berbagai wilayah, terus bermunculan suara-suara kritis atas kebijakan maupun praktik otoriter negara.
Untuk itu, Amnesty mendesak negara kembali menjadikan hak asasi manusia, sebagai prioritas utama.
Bukan hanya agar menjamin kebebasan politik seperti berekspresi dan berkumpul tanpa ancaman, tapi juga mewujudkan keadilan sosial.
Yaitu, melalui kebijakan sosial ekonomi berbasis partisipasi publik yang bermakna dan inklusif.[nnh]